HULU - HILIR MENGKOTA
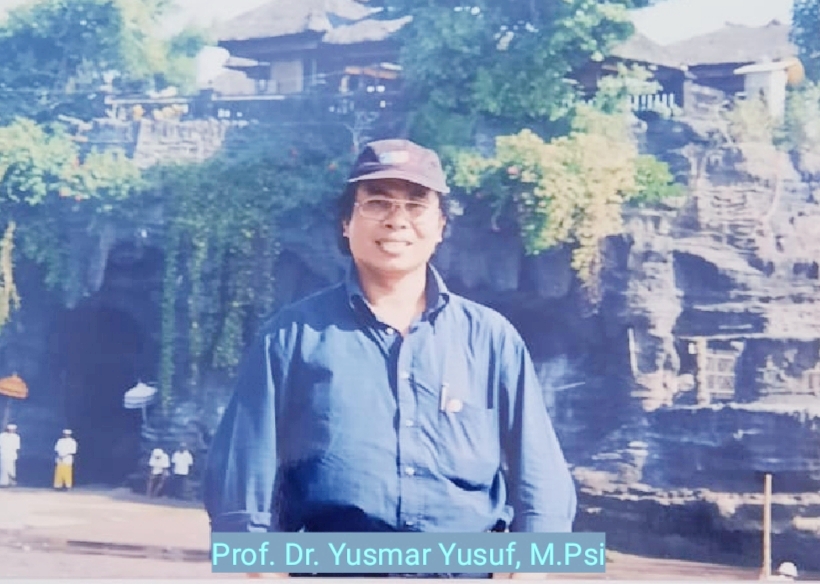
By: Yusmar Yusuf*)
Agak senyap. Dulu, kota ini amat berderap dengan segala hempasan aktivitas skala nasional dan internasional. Sejumlah event yang hadir di kota ini dulu, tak lepas dari peran pemerintah Provinsi yang memposisikan Pekanbaru sebagai kota unggulan di Sumatera selain Medan dan Palembang untuk destinasi konferensi. Namun, jika dikritisi, segala event dan konferensi itu hanya berdampak kecil terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan dalam skala besar. Memang hotel bertumbuhan, diikuti dengan restoran, tempat-tempat hiburan, pasar bergairah. Akan tetapi, pengadaan infrastruktur perkotaan seperti jaringan air, listrik dan jalan raya tidak berjalan secara masif. Yang diurus setakat jalan Sudirman dan mempersolek bandara Sultan Syarif Kasim II. Selebihnya terbiarkan.
Kini, walau tak segemuruh satu dekade silam, namun pembangunan perkotaan berdenyar di kawasan pinggiran, Tenayan Raya dan sedikit di pesisir sungai Siak. Serempak dengan kenyataan itu, taman kota kian semrawut, lampu penerang jalan dan taman kian malap, masai dan padam, tak terurus. Jalan utama dan arteri kian menyempit. Pertumbuhan kenderaan bermotor (terutama roda dua) mengalami booming luar biasa. Berdampak terhadap kenyaman berlalu lintas dan sistem perparkiran di ruas-ruas utama perkotaan. Lalu lintas teramat kacau dan terkesan “jorok”. Para pengendara, baik roda dua dan roda empat tanpa segan silu lagi melakukan tindakan melawan arus pada sebuah ruas jalan yang hingar-bingar. Gaya melawan arus ini dilakukan secara sadar dan tanpa beban, dengan kecepatan tinggi. Seakan-akan mengenderai dengan aturan yang benar. Sebaliknya, kita yang mengenderai mengikut aturan sebenarnya, salah-salah bisa disergah dan dipelototi oleh para pengendera lawan arus ini. Terjadi disorientasi ruang bagi hampir seluruh warga kota, ketika mereka sedang berada di jalan raya.
Aturan jalur searah pun tak pernah ditaati. Mengambil dan menurunkan penumpang di tengah jalan, parkir seenaknya di persimpangan, di ruas sempit persimpangan, di depan pasar, penurunan bukit kecil, di tengah jembatan, kerap dan dianggap normal-normal saja. Sehingga kita tak bisa menyebut, mana yang salah dan mana yang benar dalam berlalu lintas dan tertib perparkiran. Terhidang gejala anomali, ketiadaan nilai yang dijadikan gayutan bersama. Kita mempertonton kerendahan akal budi dan kedisiplinan, kerendahan akhlak sosial di jalanan, sekaligus tak pernah bertoleransi dengan kebenaran. Kita menjadi wakil dari bangsa dan budaya yang bangga menabrak aturan, merasa paling jumawa, paling ditakuti jika berlaku garang di jalan raya. Di sini, segalanya bisa ditumpah; sampah amarah dan sumpah seranah. Semua itu bolehlah dikategorikan sebagai sampah segala sampah. Induknya sampah.
Mengkotakah kita? Sama sekali belum. Kita baru numpang hidup di kota, dengan pemikiran liar rimba raya. Kita memang tinggal di kota, namun dengan tabiat dan perilaku murahan serba kampungan, merasa benar sendiri, tak menimbang kehadiran orang-orang lain yang juga memiliki hak yang sama dalam penggunaan jalan raya dan fasilitas perkotaan lainnya. Peristiwa mengkota itu (urbanized) adalah fenomena pemikiran, sejumlah gagasan yang ingin berubah melalui pemanfaatan orang-orang lain sekaligus bertenggang-rasa dengan sejumlah kelainan. Dalam idiom lain, bisa disebut sebagai ikhtiar mengolah ‘kelainan’, menjadi taman indah dalam sebuah penyerbukan silang yang amat produktif dan dirindukan. Melalui jalan inilah sebuah kota akan menuju ke suasana hidup yang ‘berbahagia’. Kita pun tak merindukan kota berderap, apakah itu kegiatan pemerintah dan rakyat biasa, namun kegiatan yang bergetar itu hendaklah mempertimbangan kemajuan akal budi dan kebudayaan dalam peristiwa ‘meng-kota’ (urbanized). Mampu kah? Ya, pemimpin di atas ratarata. Itu jawabannya.
Toleransi ruang, terutama ruang hijau terbuka, juga menjadi parameter mengkota. Semua ruang publik yang bisa diakses warga, harus menjadi tempat interaksi, mendewasakan aspek tenggang rasa publik, mengenal rimbunnya keragaman (pluralisme), sebuah keniscayaan. Kota itu sendiri bawaannya adalah jamak, ragam atau plural dari berbagai macam sudut dan segi. Bukan dunia yang serba seragam. Toleransi bangunan perkotaan yang fungsional untuk kawasan bisnis dan pemukiman juga menjadi pertimbangan peristiwa meng-kota itu. Kawasan pendidikan yang terpisah dengan kawasan bisnis. Kawasan bisnis premium tidak dihiruk-pikukkan oleh tampilan tenda-tenda badwi semrawut dan mengganggu pandangan mata sekaligus mengusik estetika ruang kota. Penataan lidah bangunan yang tak menjilat dahi garis pejalan kaki (trotoar); mendorong semua orang dan konsumen untuk berjalan kaki menuju pusat-pusat belanja. Bukan langsung parkir di depan toko dan gerai.
Kaidah yang terselip dari aktivitas jalan kaki itu; menyehat dan membugarkan warga, pembentukan fisik liat, sekaligus ruang sliaturahmi antar manusia yang berlalu lalang di sepanjang arkade dan garis-garis parkir menjelang tiba di toko atau gerai, membentuk ruang taman perkotaan yang diisi oleh orang-orang yang bergerak, aktif, tak pasif. Menanda kota itu hidup. Membentuk perilaku warga yang tak manja dalam gerak tubuh. Sebab, manusia Indonesia termasuk orang yang malas berjalan kaki. Dan tak pernah mendapatkan manfaat apa pun dari kisah berjalan kaki.
Semua ihwal ini bisa terjadi dan mewabah sebagai virus positif bagi warga kota, ketika rancangan infrastruktur dan penegakan “hukum” publik yang konsisten, membangun budaya malu dalam melanggar aturan publik yang telah disepakati bersama. Rancangan infrastruktur yang ramah bagi gerak pejalan kaki dengan sendirinya menuntut kemampuan pemerintah, membuka ruang dialog dengan para perencana kota yang lihai. Kanal komunikasi antara pemegang kuasa dengan para perancang kota dan budayawan atau seniman, harus menghindari kanal instruksi sepihak. Lakukan secara dialogis dan berterusan, sehingga melahirkan kematangan desain demi kepentingan publik. Bahwa ada beberapa ruas di kota ini dirancang dalam kesadaran human scale (terengkuh dalam peristwa gerak kaki manusia yang berjalan).
Mengkota? Tak ada yang tak bisa dilakukan, jika kita mau memulainya dengan dialog pada tataran rendah (low level-context); sampai tataran menengah (medium), bahkan bisa mencapai dialog tataran tinggi (high level-context). Semua perkakas ini tersedia di sebuah kota yang mengakungaku metropolitan itu. Jika tidak? Maka kita hanya menerima warisan kota dalam bentuk fisiknya saja yang metropolitan, tetapi warga yang mengisi kota “bentuk” metropolitan itu diisi oleh sekumpulan gerombolan liar (savage) atau malah sekumpulan pesukuan liar (tribes).
----------'----------------------
Prof. Dr.YUSMAR YUSUF, M.Psi., Guru Besar Sosiologi, Universitas Riau.
